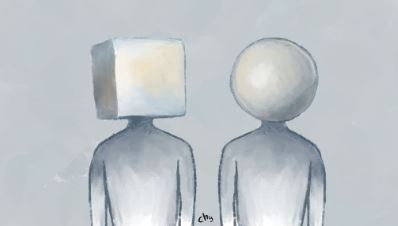santrimillenial.id – Adanya dua kubu yang saling bertentangan seringkali dianggap menimbulkan sesuatu yang negatif. Padahal perbedaan pendapat wajar terjadi pada ruang lingkup sosial manusia. Mereka tidak bisa dipaksa untuk memiliki pendapat dan pemikiran yang sama.
Allah pun dalam menciptakan sesuatu pasti saling berpasangan, bahkan saling bertentangan. Seperti laki-laki dan perempuan, manusia dan jin, baik dan buruk. Bahkan ulama pun membuat madzhab sendiri-sendiri; bukti dari perbedaan pendapat mereka. Hal ini adalah sebuah Rahmat dan tidak akan bisa dihindari.
Tetapi, dalam panggung politik, para tokoh dan masyarakat mencemaskan adanya polarisasi politik. Masyarakat menganggap, bahwa polarisasi adalah sebuah ancaman dan dapat memecah belah rakyat. Munculnya “civil dan uncivil”, “moderat dan radikal”, “liberal dan konservatif”, “maupun pluralism dan gerakan transnasiol” memperkuat narasi ploralisme.
Pada masa setelah terbunuhnya Khalifah Ustman bin Affan, kondisi politik pada masa itu tidak kondusif. Ditambah masyarakat yang terpolarisasi menjadi tiga kubu yang saling bertentangan.
Ketiga kelompok itu adalah kelompok Syi’ah; kelompok yang setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelompok yang setia kepada Muawiyah, dan kelompok sempalan dari tentara Ali yang kemudian dikenal sebagai Khawarij.
Perpecahan ini terjadi karena perbedaan ijtihad antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah balasan qishah atas pembunuhan Sayyidina Ustman. Sayyidina Ali berpendapat, bahwa dalam mengeksekusi pelaku tidak boleh gegabah, karena kondisi politik yang belum kondusi. Ditambah, pelaku belum jelas identitasnya. Sedangkan Muawiyah menginginkan untuk segera mengeksekusi pelaku pembunuhan Sayyidina Ustman.
Ali menganggap sikapnya sudah benar dan Muawiyah salah. Begitupun sebaliknya. Muawiyah menganggap sikapnya sudah benar dan Ali salah. Hal ini yang memicu peperangan antara keduanya.
Iqbal F Dwiranda di dalam opini berjudul “Realitas polarisasi politik” yang dimuat di kompas.id, berpendapat bahwa polarisasi politik sejatinya merupakan proses, bukan kondisi statis. Masih dalam opini yang sama, Iqbal juga mengatakan bahwa selama polarisasi terjadi pada tingkat yang wajar itu akan berguna untuk membedakan platform partai politik yang bersaing dan untuk mendorong warga negara lebih berpartisipasi dalam momen-momen politik krusial seperti pengambilan kebijakan dan pemilihan pimpinan politik.
Polarisasi politik menurut Jennifer McCoy dkk(2022) dalam Reducing Pernicious Polarization; lebih dipahami sebagai proses, keadaan keseimbangan, dan strategi politik.
Dalam menghadapi masyarakat yang terpolarisasi dalam pentas politik, kita seharusnya selalu berprasangka baik pada setiap kelompok. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menyimpulkan dan mencela kelompok yang menurut pandangan kita salah.
Pendapat seseorang tidak harus kita taati. Kita berhak memilih pendapat yang menurut kita benar. Bahkan kita juga bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri. Kita juga tidak berhak untuk memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Bahkan, Nabi saja tidak berhak. “Kamu tidak punya hak memaksa mereka”, kata Al-Qur’an (QS al- Ghaasyiyah (88): 22).
Bahkan, di dalam urusan keimanan pun, Allah membebaskan manusia untuk memilih. “Tidak boleh ada pemaksaan dalam memilih agama. Telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah.” (QS. Al-Baqarah (2): 256).
Jadi, wajar jika dalam pentas politik mereka, terutama para tokoh politik mempunyai ijtihadnya masing-masing dalam mengawal politik 2024 mendatang.
Mendekati pesta politik, kita juga harus fokus dengan apa yang akan kita pilih. Jangan teralihkan dengan konflik-konflik politik yang tidak akan ada habisnya. Polarisasi ini akan terus terjadi, selama bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis. Apapun hasilnya nanti, adalah pilihan mayoritas masyarakat yang tidak dapat kita hindari.
Penulis: Putri Nadillah
Sumber gambar: kompas.id